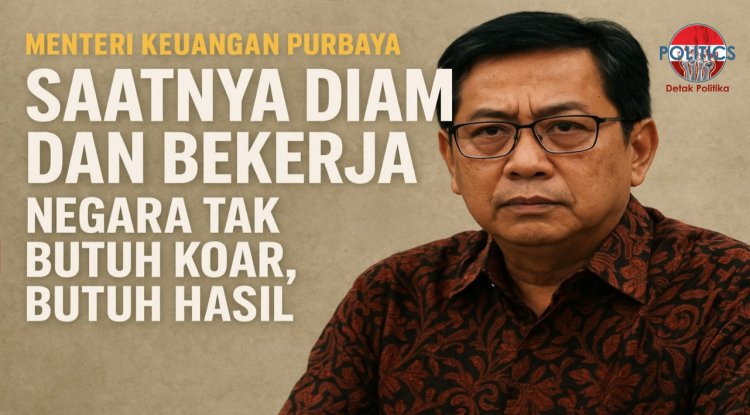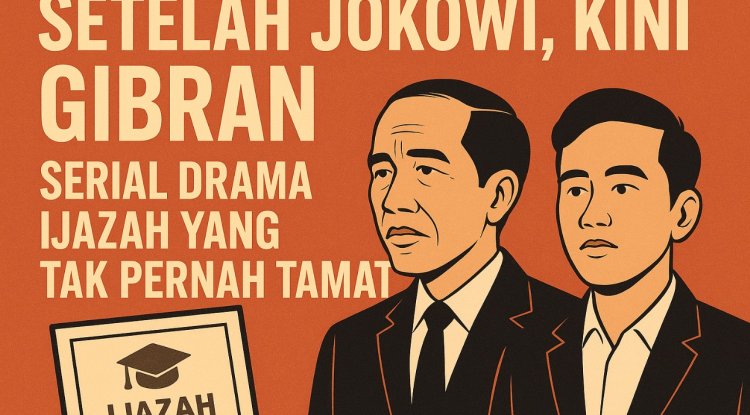Masa Depan Bertani Telah Tiba: Menata Pertanian Presisi Berbasis Internet of Things (IoT) di Tengah Krisis Agrikultur Indonesia
Masa Depan Bertani Telah Tiba: Menata Pertanian Presisi Berbasis Internet of Things (IoT) di Tengah Krisis Agrikultur Indonesia

Penulis: Tambun Sihotang, S.Agr., M.Agr. | Peneliti Utama Bidang Pertanian Detak Politik
detakpolitik.com, JAKARTA - Dalam dekade terakhir, dunia pertanian dihadapkan pada tantangan kompleks yang menuntut inovasi di luar pendekatan tradisional. Perubahan iklim, pertumbuhan populasi, degradasi lahan, dan keterbatasan sumber daya air memaksa sektor pertanian beradaptasi secara cepat. Salah satu solusi yang kini banyak dibicarakan dan mulai diterapkan secara bertahap adalah pertanian presisi berbasis Internet of Things (IoT) sebuah perpaduan antara teknologi digital dan praktik pertanian yang menjanjikan peningkatan efisiensi, keberlanjutan, dan produktivitas pertanian secara signifikan. Inilah revolusi hijau baru yang berakar pada data dan konektivitas.
Pertanian presisi, pada dasarnya, adalah sistem produksi tanaman atau ternak yang didasarkan pada prinsip pengelolaan yang tepat: tepat waktu, tepat lokasi, tepat jumlah, dan tepat input. Ketika prinsip ini dikawinkan dengan teknologi IoT, lahirlah sistem pertanian yang tidak lagi hanya mengandalkan intuisi atau kebiasaan turun-temurun, tetapi berbasis pada data real-time yang akurat. Sensor tanah, sensor kelembapan, kamera multispektral, stasiun cuaca mini, dan alat pengendali otomatis kini bukan lagi eksklusif milik negara maju. Di banyak titik pertanian Indonesia, teknologi ini perlahan mulai dikenalkan meski belum massif dan menunjukkan potensi yang luar biasa untuk mengubah wajah pertanian kita.
Masalah paling mendasar dalam pertanian konvensional selama ini adalah ketidakpastian. Petani sulit memprediksi kapan waktu tanam terbaik, berapa banyak pupuk yang harus diberikan, atau kapan serangan hama akan datang. Akibatnya, produktivitas sering kali stagnan, biaya produksi tinggi, dan hasil panen tidak optimal. Lebih jauh lagi, penggunaan input pertanian seperti pupuk dan pestisida sering kali tidak efisien, bahkan berdampak negatif terhadap lingkungan. Di sinilah pertanian presisi berbasis IoT memainkan peran vital. IoT bekerja dalam sistem pertanian presisi melalui penggunaan berbagai sensor yang diletakkan di lapangan—sensor kelembapan tanah, suhu udara, kadar pH, intensitas cahaya matahari, hingga kamera multispektral untuk citra tanaman. Sensor-sensor ini mengumpulkan data yang dikirim secara otomatis ke server atau cloud, kemudian dianalisis oleh sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) atau algoritma pemrosesan data. Hasilnya, petani dapat mengetahui secara real-time kondisi lahan dan tanaman, serta memperoleh rekomendasi tindakan yang tepat, seperti kapan menyiram, berapa dosis pupuk yang dibutuhkan, atau apakah tanaman menunjukkan gejala stres.
Bayangkan, seorang petani jagung di daerah Deli Serdang yang sebelumnya mengandalkan perkiraan cuaca dari televisi lokal kini dapat memperoleh informasi aktual dari sensor cuaca mandiri yang terpasang di lahannya. Ia tahu kapan akan turun hujan, seberapa besar curahnya, dan bagaimana menyesuaikan jadwal tanam serta dosis irigasi. Di lahan yang sama, sistem irigasi otomatis bisa diatur agar menyiram hanya ketika kelembapan tanah turun di bawah ambang batas tertentu, menghemat air hingga 40% dibandingkan metode manual. Di tengah krisis air dan kekeringan yang makin sering melanda daerah-daerah pertanian, efisiensi semacam ini bukan lagi keunggulan tambahan, melainkan kebutuhan pokok.
Lebih dari itu, pertanian presisi juga membuka kemungkinan deteksi dini terhadap penyakit dan serangan hama. Kamera multispektral yang dipasang di drone atau tiang pemantau dapat mendeteksi gejala stres pada tanaman sejak dini, bahkan sebelum terlihat oleh mata manusia. Dengan bantuan kecerdasan buatan (AI), sistem akan mengolah data visual dan memberikan peringatan kepada petani melalui aplikasi. Dalam waktu singkat, petani dapat mengambil tindakan spesifik hanya pada area yang terdampak, bukan menyemprot seluruh lahan dengan pestisida. Ini mengurangi biaya, menjaga ekosistem, dan tentu saja, meningkatkan kualitas produk pertanian yang lebih sehat.
Namun, transformasi menuju pertanian presisi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di Indonesia, tantangan terbesarnya bukan pada teknologi itu sendiri, tetapi pada kesiapan sumber daya manusianya. Banyak petani belum familiar dengan perangkat digital, apalagi mengoperasikan sistem berbasis IoT. Literasi teknologi pertanian di pedesaan masih rendah, sementara ketersediaan sinyal internet yang stabil di banyak kawasan sentra produksi pertanian juga masih menjadi kendala. Belum lagi soal biaya awal yang cukup tinggi untuk pengadaan perangkat-perangkat canggih tersebut.
Di sinilah peran negara dan institusi pendidikan menjadi krusial. Pemerintah tidak bisa hanya menyuarakan modernisasi pertanian sebagai slogan tanpa menyediakan ekosistem pendukungnya. Pelatihan teknologi pertanian berbasis digital harus menjadi program wajib di setiap balai penyuluhan. Penyuluh pertanian lapangan harus dibekali kemampuan teknis untuk mengenalkan, mengoperasikan, dan merawat perangkat IoT. Di sisi lain, universitas dan politeknik pertanian harus menyesuaikan kurikulum mereka agar lebih responsif terhadap kebutuhan zaman: bukan hanya mencetak lulusan yang mampu bertani, tetapi juga mampu memanfaatkan dan mengembangkan teknologi canggih dalam bertani.
Koperasi tani dan kelompok tani juga bisa menjadi ujung tombak adopsi teknologi ini. Alih-alih membiarkan petani individu membeli perangkat IoT sendiri, pendekatan kolektif berbasis komunitas jauh lebih efisien. Pemerintah daerah, BUMDes, atau bahkan startup pertanian bisa menyediakan skema sewa perangkat IoT dengan biaya yang terjangkau, sehingga teknologi ini bisa dinikmati oleh petani kecil. Jika dikelola dengan baik, potensi ini bahkan dapat membuka lapangan kerja baru di bidang jasa layanan pertanian digital: mulai dari teknisi perangkat, analis data pertanian, hingga konsultan pemupukan presisi.
Di berbagai negara, pertanian presisi berbasis IoT telah terbukti meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan. Di Belanda, misalnya negara kecil dengan lahan terbatas namun menjadi eksportir produk hortikultura terbesar dunia penggunaan teknologi presisi memungkinkan mereka memaksimalkan setiap meter persegi lahan dengan efisiensi tinggi. Di India, negara dengan karakter petani kecil dan lahan sempit seperti Indonesia, teknologi IoT mulai diadopsi secara luas melalui kerja sama antara startup agritech dan pemerintah. Indonesia tidak bisa lagi terus tertinggal.
Jika diterapkan secara masif dan inklusif, pertanian presisi bisa menjadi solusi terhadap berbagai tantangan mendasar pertanian Indonesia. Ia bisa membantu mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, mengurangi emisi karbon, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Teknologi ini juga membuka peluang besar bagi generasi muda yang selama ini memandang pertanian sebagai profesi kotor, melelahkan, dan tak menjanjikan. Dengan kehadiran sistem berbasis data, pertanian kini menjadi arena yang menarik bagi mereka yang menyukai teknologi, analitik, dan inovasi. Petani modern bukan lagi mereka yang menggenggam cangkul dan menatap langit, tetapi mereka yang memegang tablet dan membaca dashboard cuaca dan nutrisi tanah.
Namun perlu kita sadari bersama, pertanian presisi bukanlah tujuan akhir, melainkan jembatan menuju sistem pertanian yang lebih resilien, inklusif, dan berkelanjutan. Teknologi hanyalah alat, dan alat ini hanya seefektif manusia yang menggunakannya. Maka keberhasilan implementasi pertanian berbasis IoT tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak sensor yang dipasang di sawah, tetapi juga seberapa dalam pemahaman dan kesadaran kita tentang pentingnya mengelola pertanian dengan prinsip ilmiah, efisien, dan peduli terhadap lingkungan.
Kita hidup di masa ketika suhu semakin panas, tanah semakin miskin, dan jumlah petani semakin berkurang. Sementara itu, jumlah mulut yang harus diberi makan terus bertambah. Dalam konteks ini, pertanian presisi bukan pilihan, tetapi keniscayaan. Indonesia harus bangkit dari ketertinggalannya dalam hal inovasi agrikultur. Kita tidak boleh terus mengandalkan cara-cara lama dalam menghadapi tantangan baru.
Sumatera Utara, yang selama ini dikenal dengan kekayaan lahan dan keragaman komoditas pertaniannya, bisa menjadi pelopor transformasi ini. Kabupaten-kabupaten seperti Karo, Simalungun, Deli Serdang, dan Humbang Hasundutan dapat dijadikan pilot project pertanian presisi berbasis IoT, dengan dukungan dari universitas lokal seperti Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas HKBP Nommensen, dan institusi pertanian lainnya. Jika dilakukan secara serius dan terencana, kita tidak hanya menyelamatkan pertanian daerah dari kehancuran ekologis, tetapi juga menjadikannya contoh bagi daerah lain.
Kini saatnya kita bertindak. IoT bukan sekadar tentang koneksi internet dan sensor digital. Ia adalah tentang konektivitas yang lebih dalam antara manusia dan alam, antara teknologi dan tradisi, antara masa lalu dan masa depan pertanian Indonesia. Maka mari kita siapkan tanah, bukan hanya untuk ditanami benih, tetapi juga untuk ditanami pengetahuan dan inovasi.
Masa depan bertani telah tiba. Dan ia menunggu untuk kita sambut, dengan tangan terbuka dan pikiran yang tercerahkan.
(Tambun Sihotang, S.Agr., M.Agr.)
Apa Reaksi Anda?