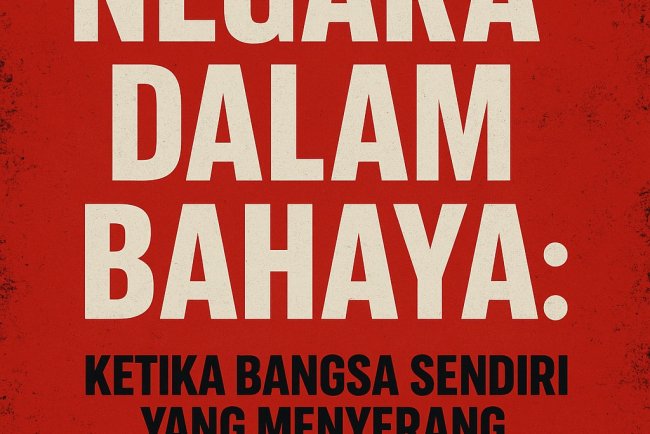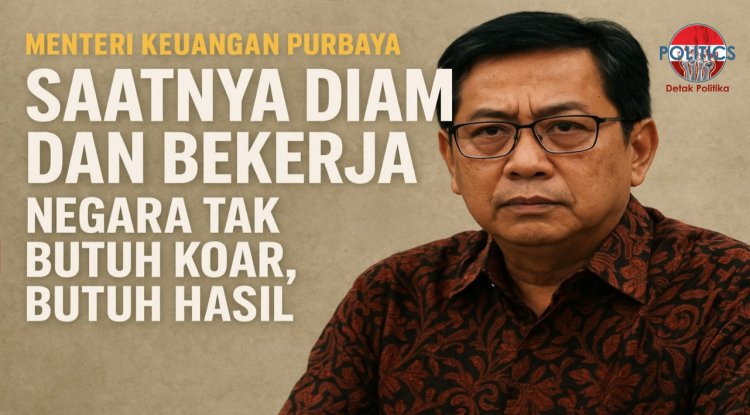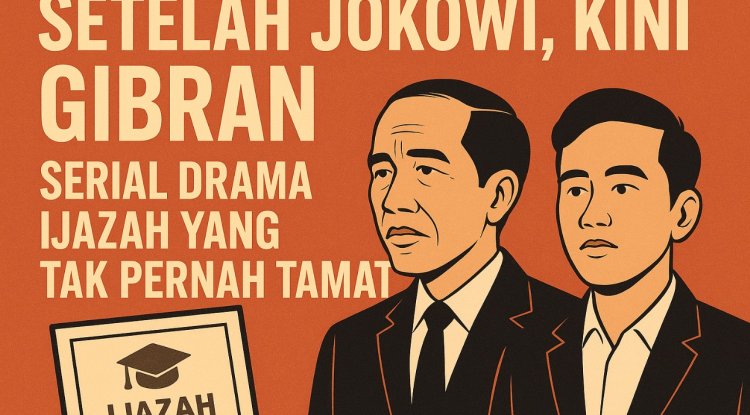Antara Aspirasi Rakyat, Kepentingan Elite, dan Luka Ekonomi: Membaca Ulang Dampak Gelombang Demonstrasi di Indonesia
Antara Aspirasi Rakyat, Kepentingan Elite, dan Luka Ekonomi: Membaca Ulang Dampak Gelombang Demonstrasi di Indonesia

Ditulis: Hengki Tamando Sihotang
detakpolitik.com, Jakarta - Gelombang demonstrasi yang terjadi beberapa hari terakhir kembali membuka wajah rapuh relasi antara rakyat, negara, dan kekuasaan di Indonesia. Dari Jakarta hingga kota-kota lain di berbagai provinsi, jalan-jalan kembali menjadi panggung bagi masyarakat untuk menyuarakan keresahannya. Namun sebagaimana yang sering terjadi dalam sejarah bangsa ini, suara rakyat kerap dibayar mahal: kerusakan fasilitas umum, korban luka, hingga luka ekonomi yang tidak tampak tetapi meresap ke dalam kehidupan sehari-hari.
Pernyataan Gubernur DKI Jakarta per pagi ini menyebutkan bahwa kerugian untuk memulihkan fasilitas umum yang rusak mencapai 50 miliar rupiah. Angka itu tentu bukan sekadar nominal di atas kertas; ia adalah representasi dari berapa banyak dana publik yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan dasar, tetapi harus kembali dipakai untuk memperbaiki halte bus yang terbakar, pagar jalan yang roboh, atau lampu lalu lintas yang hancur. Belum lagi jika dihitung biaya perawatan korban luka, kompensasi tenaga medis, serta biaya sosial lain yang mengalir deras pasca demonstrasi.
Namun kerugian tidak hanya berhenti di situ. Pasar modal Indonesia juga bereaksi cepat. IHSG tercatat turun 2% pada hari terjadinya demonstrasi besar. Bagi sebagian orang, angka ini tampak kecil dan sementara. Tetapi bagi investor, baik lokal maupun asing, pergerakan indeks adalah barometer kepercayaan terhadap stabilitas politik dan ekonomi. Penurunan IHSG adalah bukti bahwa pasar modal merespons demo dengan penuh kekhawatiran. Dalam bahasa sederhana, para pelaku pasar menilai ada ketidakpastian yang membayangi Indonesia. Dan sebagaimana hukum pasar, ketidakpastian berarti risiko, dan risiko berujung pada pelepasan aset. Lagi-lagi yang paling terdampak adalah rakyat kecil: mereka yang menabung dalam bentuk saham atau reksa dana melihat nilai portofolionya menyusut, sedangkan pemerintah harus bekerja lebih keras menjaga citra stabilitas ekonomi di mata dunia.
Presiden Prabowo sendiri dalam keterangannya menyebut bahwa demonstrasi kali ini tidak sepenuhnya murni. Ada dugaan campur tangan sekelompok orang yang ingin mengadu domba dan membuat kekacauan. Pernyataan semacam ini tentu bukan hal baru dalam sejarah politik Indonesia. Narasi mengenai “tangan-tangan gelap” atau “aktor-aktor tak terlihat” kerap muncul setiap kali terjadi gelombang massa. Bisa jadi benar, bisa juga sekadar framing politik. Namun satu hal yang pasti: setiap demonstrasi besar di negeri ini tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia selalu berakar pada persoalan ekonomi, ketidakadilan, dan kebijakan publik yang dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat.
Di atas kertas, ekonomi Indonesia memang tumbuh. Data resmi menunjukkan bahwa di kuartal lima, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12%. Angka ini dipuji sebagai pencapaian yang stabil di tengah kondisi global yang penuh tantangan. Namun, pertumbuhan itu nyatanya dibayangi oleh berbagai persoalan. Salah satunya adalah kenaikan tunjangan bagi para wakil rakyat yang justru dipandang sebagai pemantik awal keresahan publik. Bayangkan, di saat masyarakat berjuang keras memenuhi kebutuhan pokok di tengah harga yang terus naik, para wakil rakyat justru menaikkan tunjangan dengan nominal yang dianggap fantastis. Kontras semacam ini menciptakan jurang psikologis antara rakyat dan elit, yang kemudian memicu amarah publik.
Kemarahan ini semakin membara ketika data-data ekonomi menunjukkan adanya ketidaksinkronan. Berdasarkan ulasan Kompas, rasio tabungan masyarakat dari Juli ke Juni justru menurun dari 14,1% menjadi 13,7%. Angka yang sekilas tampak kecil ini sesungguhnya menyimpan pesan besar: masyarakat terpaksa menggerus tabungannya untuk bertahan hidup. Dalam teori ekonomi, penurunan rasio tabungan adalah tanda bahwa penghasilan masyarakat tidak cukup untuk menutup kebutuhan konsumsi. Artinya, klaim pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% tidak sepenuhnya dirasakan oleh rakyat kecil. Pertumbuhan itu mungkin nyata dalam laporan makro, tetapi rapuh dalam kenyataan mikro.
Lebih jauh lagi, rasio pendapatan masyarakat untuk membayar utang naik dari 10,5% pada April menjadi 10,8% pada Juni. Ini adalah angka yang sangat mengkhawatirkan. Ia menandakan bahwa masyarakat bukan hanya hidup dari tabungan, tetapi juga semakin bergantung pada utang. Jika fenomena ini terus berlanjut, maka apa yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi sesungguhnya adalah pertumbuhan semu. Rakyat tidak menikmati hasil pembangunan, melainkan hanya bertahan dengan cara menggali lubang untuk menutup lubang.
Dalam konteks inilah, demonstrasi menemukan panggungnya. Ia bukan sekadar reaksi spontan terhadap satu kebijakan, melainkan akumulasi keresahan struktural: harga kebutuhan pokok yang terus naik, pajak yang semakin menjerat, tabungan yang bisa dibekukan jika tak ada transaksi selama tiga bulan, bisnis online yang kini dikenai pajak, hingga ketidakpastian kerja di era digital. Ketika semua tekanan itu menumpuk, rakyat kecil merasa tidak lagi punya saluran aspirasi selain turun ke jalan.
Namun, seperti yang sering terjadi, gerakan rakyat yang lahir dari keresahan otentik sering kali dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Inilah yang menjadi ironi sekaligus tragedi politik Indonesia. Rakyat turun dengan niat menyuarakan beban hidup, tetapi elite politik atau kelompok berkepentingan melihatnya sebagai peluang untuk memperbesar pengaruh atau mengacaukan stabilitas. Tidak heran jika Presiden Prabowo menuding adanya upaya adu domba.
Di sisi lain, pemerintah dan aparat juga kerap terjebak dalam pola lama: merespons demonstrasi dengan pendekatan keamanan semata. Kerusuhan dipukul rata sebagai gangguan stabilitas, padahal di balik kerumunan massa terdapat jeritan ekonomi yang nyata. Rakyat bukan sekadar “massa pengacau”, tetapi manusia yang merasa dipinggirkan oleh kebijakan. Jika negara hanya menjawab dengan represi, maka siklus ketidakpercayaan semakin dalam, dan demo akan terus berulang dalam berbagai bentuk.
Di titik ini, kita bisa bertanya: apa sebenarnya yang sedang dipertaruhkan? Apakah sekadar perbaikan fasilitas umum yang rusak senilai 50 miliar? Apakah sekadar menjaga agar IHSG tidak jatuh terlalu dalam? Ataukah yang dipertaruhkan jauh lebih besar: kepercayaan rakyat terhadap negara?
Mari kita kembali pada fakta: pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,12% hanyalah angka jika tidak mampu menjawab kenyataan bahwa rakyat harus hidup dari tabungan dan utang. Angka-angka makro tidak boleh membutakan kita dari realitas mikro. Ketika rasio tabungan menurun dan rasio pembayaran utang melonjak, itu artinya rakyat sedang terhimpit. Dan ketika di saat yang sama, wakil rakyat justru menaikkan tunjangan, maka wajar jika rakyat merasa dikhianati.
Sayangnya, fenomena ini bukan kali pertama terjadi. Dalam sejarah Indonesia, kita sudah berkali-kali menyaksikan bagaimana jurang antara angka makro dan realitas mikro melahirkan gejolak sosial. Tahun 1998 adalah contoh paling nyata: ekonomi Indonesia tumbuh di atas kertas, tetapi krisis moneter membuat rakyat kehilangan pekerjaan, harga-harga melambung, dan pada akhirnya rakyat turun ke jalan. Tuntutan saat itu bukan hanya ekonomi, tetapi juga politik. Kini, meskipun konteksnya berbeda, kita melihat pola yang serupa: rakyat merasa ekonomi tidak berpihak pada mereka, sehingga jalanan kembali menjadi arena protes.
Di sisi lain, fenomena menurunnya tabungan dan meningkatnya utang rumah tangga juga harus dibaca sebagai tanda bahaya jangka panjang. Negara yang sehat adalah negara yang warganya bisa menabung, bukan sebaliknya. Ketika rakyat terpaksa hidup dengan menggerus tabungan atau mengandalkan utang, itu berarti daya beli mereka sesungguhnya melemah. Dan jika daya beli melemah, pertumbuhan ekonomi 5,12% hanya akan menjadi angka semu yang tidak berkelanjutan.
Maka, demonstrasi kali ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah. Alarm bahwa kebijakan ekonomi tidak bisa hanya diukur dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari seberapa nyata rakyat kecil merasakan manfaatnya. Alarm bahwa komunikasi publik tidak boleh hanya diisi dengan klaim pencapaian, tetapi juga dengan kesediaan mendengar keluhan. Alarm bahwa keadilan sosial bukan slogan dalam konstitusi, melainkan hak nyata yang harus diwujudkan.
Tentu saja, kerusakan fasilitas umum, jatuhnya korban, dan turunnya IHSG adalah kerugian besar. Tetapi lebih besar dari itu adalah kerugian sosial-politik jika pemerintah gagal membaca makna di balik demonstrasi. Jika keresahan rakyat hanya dijawab dengan narasi “ada pihak yang ingin mengadu domba”, maka esensi suara rakyat akan hilang di balik framing politik. Padahal, suara rakyat adalah fondasi dari demokrasi itu sendiri.
Dalam situasi seperti ini, kita perlu kembali ke pertanyaan mendasar: apa arti pembangunan? Apakah pembangunan berarti gedung-gedung tinggi, jalan tol baru, dan angka pertumbuhan yang stabil? Ataukah pembangunan berarti kehidupan rakyat yang lebih layak, kemampuan untuk menabung, bebas dari lilitan utang, dan merasa didengar oleh wakil yang mereka pilih?
Opini publik yang lahir dari demonstrasi ini sesungguhnya sederhana: rakyat menuntut keadilan ekonomi dan kesetaraan. Mereka ingin merasa bahwa negara hadir bukan hanya untuk segelintir elite, tetapi untuk semua. Mereka ingin kebijakan yang tidak hanya berpihak pada pasar, tetapi juga pada dapur rumah tangga mereka.
Jika pemerintah dan para wakil rakyat gagal menjawab tuntutan sederhana ini, maka demonstrasi demi demonstrasi akan terus terjadi. Jalanan akan terus dipenuhi oleh suara-suara yang merasa diabaikan. Dan setiap kali itu terjadi, kerugian materi dan sosial akan semakin membesar.
Kita tidak bisa lagi menutup mata. Angka pertumbuhan 5,12% tidak boleh menjadi tameng untuk menutupi kenyataan bahwa rakyat sedang terhimpit. IHSG turun 2% bukan sekadar sinyal pasar, tetapi juga cermin dari rapuhnya kepercayaan. Kerugian fasilitas umum 50 miliar bukan sekadar biaya perbaikan, tetapi juga simbol dari biaya politik yang harus ditanggung ketika rakyat dan negara gagal saling mendengarkan.
Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar angka. Ia membutuhkan keadilan sosial yang nyata. Ia membutuhkan wakil rakyat yang tahu diri, yang tidak menaikkan tunjangan ketika rakyat menjerit. Ia membutuhkan pemerintah yang lebih peka, yang tidak sekadar mengutamakan stabilitas makro, tetapi juga memastikan rakyat kecil bisa menabung dan hidup tanpa utang.
Demonstrasi kali ini hanyalah salah satu episode. Tetapi jika kita gagal belajar darinya, maka episode-episode berikutnya akan datang, mungkin dengan intensitas yang lebih besar. Dan ketika itu terjadi, kita bukan hanya kehilangan 50 miliar rupiah, bukan hanya kehilangan 2% di IHSG, tetapi kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga: kepercayaan rakyat terhadap negara. (hengki/dp)
Apa Reaksi Anda?