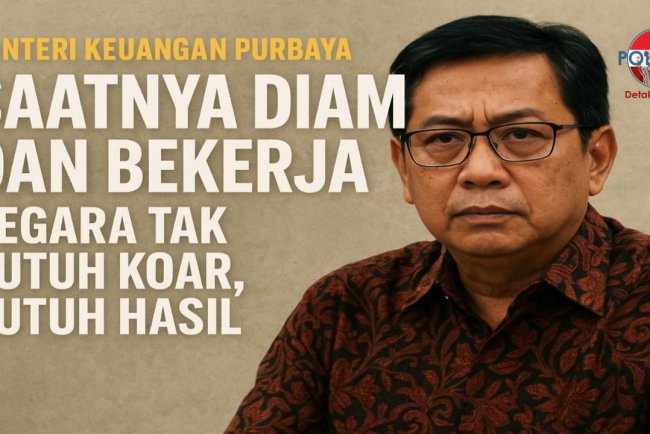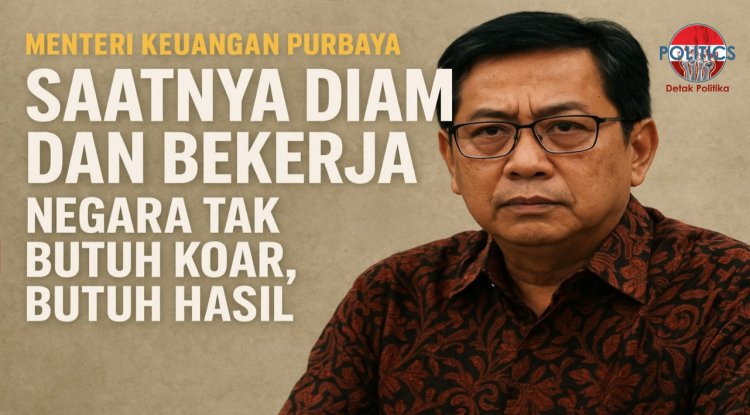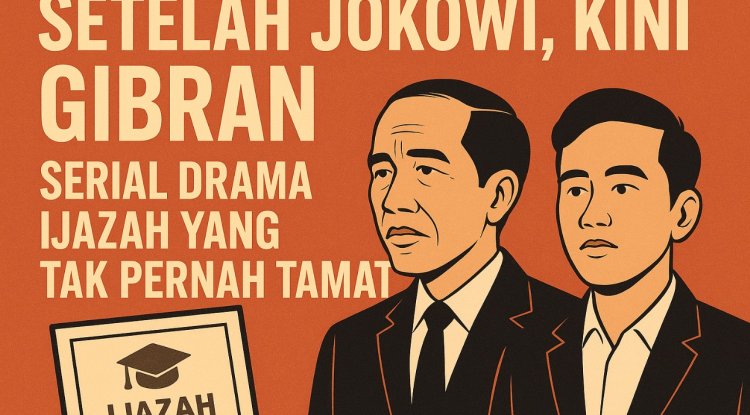Gelombang Protes dan Krisis Intelijen: Kegagalan BIN atau Kecolongan Presiden Prabowo?
Gelombang Protes dan Krisis Intelijen: Kegagalan BIN atau Kecolongan Presiden Prabowo?
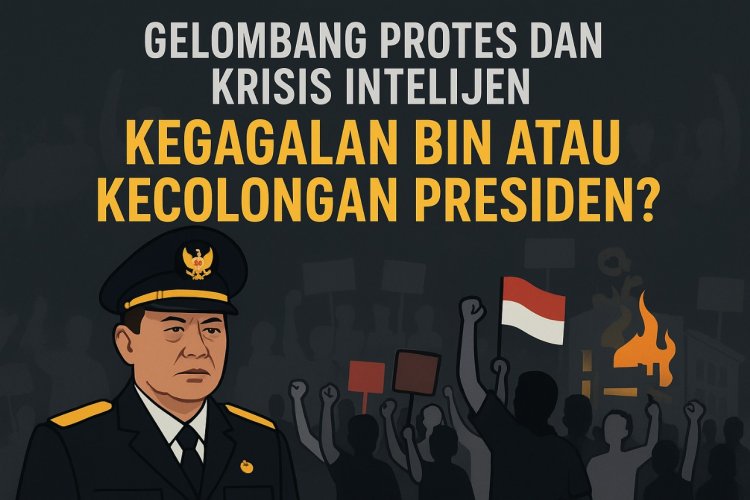
Penulis: Hengki Tamando Sihotang
detakpolitik.com, Jakarta - Berada di tengah pusaran protes yang menjalar dari Senayan hingga ke sejumlah kota besar, pertanyaan yang menggigit wajar muncul: ini kegagalan Prabowo sebagai presiden, atau kegagalan BIN sebagai penjaga “indra peraba” negara? Jawaban singkatnya: jika tujuan kita adalah mencegah korban, menjaga hak konstitusional warga, dan memulihkan kepercayaan publik, menyalahkan satu aktor saja justru menutup jalan keluar. Gelombang protes besar hampir selalu lahir dari akumulasi masalah kombinasi keputusan politik yang kontroversial, komunikasi pemerintah yang lambat, pengamanan yang gagap, ekosistem informasi yang bising, dan intelijen yang terlambat bertransformasi menjadi “aksi dini.” Di titik itu, tanggung jawab politik Presiden tidak bisa didelegasikan, sementara tanggung jawab profesional intelijen BIN maupun unsur intelijen lain tidak boleh menghilang dalam kabut komando.
Mari kita susun dulu konteks faktual paling mutakhir. Sejak 25 Agustus 2025, aksi di sekitar DPR/MPR Jakarta dipicu amarah publik atas isu tunjangan perumahan anggota DPR. Benturan terjadi; seorang pengemudi ojek daring berusia 21 tahun, Affan Kurniawan, tewas setelah tertabrak kendaraan polisi peristiwa ini menjadi titik nyala emosi kolektif dan memicu solidaritas lintas kota. Otoritas mengonfirmasi penangkapan ratusan orang di Jakarta; Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyatakan aparat akan bertindak tegas menindak pelaku kekerasan, sementara Presiden Prabowo memerintahkan penindakan dan pemulihan ketertiban. Di Sulawesi Selatan, gedung DPRD Makassar dibakar; setidaknya tiga orang tewas dan lima luka-luka. Protes menyebar ke Bandung, Surabaya, Denpasar; sejumlah kedutaan mengeluarkan imbauan agar warga menghindari kerumunan. Dalam lanskap seperti ini, rumor dan potongan video beredar cepat, memperuncing persepsi represif negara di satu sisi dan persepsi anarki massa di sisi lain. Sumber-sumber kredibel yang mengonfirmasi poin-poin tersebut dapat ditelusuri dalam laporan Reuters, Associated Press, The Washington Post, dan imbauan resmi Kedutaan AS.
Kenyataan di lapangan juga menunjukkan keluasan spektrum tindakan dari aksi damai, sweeping spontan, hingga kekerasan terhadap aset publik dan privat. Di Jakarta Utara, rumah dinas anggota DPR Ahmad Sahroni diserang; media nasional merekam kerusakan dan respon tokoh terkait. Fakta semacam ini menandakan bahwa protes tidak lagi bergerak murni dalam ranah “aspirasi di ruang publik,” tetapi telah bersentuhan dengan domain keamanan personal, sebuah tanda eskalasi yang biasanya muncul ketika kanal-kanal penyaluran aspirasi tersumbat atau kepercayaan terhadap efektivitas kanal itu melemah.
Di saat bersamaan, Komnas HAM turun memantau, membuka posko pengaduan, dan merilis temuan awal yang menyoroti pola pengendalian massa dan dugaan ekses penggunaan kekuatan, sementara kelompok masyarakat sipil seperti KontraS dan LBH Jakarta menyuarakan keprihatinan atas penangkapan massal dan menyerukan tata kelola penggunaan senjata pengendali massa yang sesuai aturan. Ini penting karena memastikan bahwa narasi negara tentang “pemulihan ketertiban” tidak meniadakan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas.
Dalam bingkai hukum, tugas, fungsi, dan posisi BIN jelas. Undang-Undang 17/2011 menempatkan fungsi intelijen pada tiga sumbu: penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dengan mandat pencegahan dan penangkalan dini ancaman terhadap keamanan nasional. BIN berada langsung di bawah Presiden dan, di samping fungsi intelijen, memegang peran koordinasi intelijen negara. Perpres 90/2012 menurunkan fungsi dan struktur BIN ke dalam unit-unit operasional: dari intel dalam negeri, kontra-intelijen, ekonomi, teknologi hingga produksi intelijen. Dengan kata lain, norma hukumnya tegas: BIN bukan sekadar pengumpul informasi, melainkan simpul yang harus memadukan produk intelijen lintas lembaga dan mendorong “aksi kebijakan” sebelum krisis membesar.
Fakta politik saat ini juga penting: sejak Oktober 2024, Letjen (Purn.) Muhammad Herindra menjabat Kepala BIN, menggantikan Budi Gunawan. Pergantian itu dan kedekatan Herindra dengan Presiden sejak di Kemenhan diharapkan memperkuat garis koordinasi antara pertahanan dan intelijen. Harapan semacam ini wajib diuji dengan kinerja, utamanya pada momen krisis seperti gelombang protes terkini.
Lalu, apakah eskalasi protes ini “kegagalan BIN” atau “kegagalan Prabowo”? Dari sudut pandang intelijen, ada empat titik rawan yang lazim menjelaskan mengapa peringatan dini tidak berujung pada pencegahan: kegagalan mendeteksi (indikator sosial-ekonomi dan politik dibaca terlambat atau dianggap noise), kegagalan menganalisis (data ada tapi sintesisnya tak tajam), kegagalan mendiseminasikan (peringatan tidak sampai ke pengambil keputusan yang tepat waktu), dan kegagalan mengeksekusi (peringatan sampai, tapi kebijakan dan sumber daya untuk “aksi dini” tidak bergerak). Empat simpul inilah yang perlu diaudit, dan auditnya tidak boleh berhenti pada BIN. Sebab ekosistem intelijen Indonesia multipusat: ada intelijen kepolisian, intelijen TNI, dan unit intelijen di banyak kementerian/lembaga. UU 17/2011 sendiri mengakui keragaman penyelenggara intelijen dan menuntut koordinasi. Ketika protes meledak, indikator “ketidakterhubungan” biasanya muncul pada koordinasi lintas-lembaga dan pada transisi dari “peringatan” ke “penataan ruang aksi” (rute, waktu, pembatasan, negosiasi, kanal aspirasi), yang merupakan domain pengamanan terbuka Polri. Dengan kata lain, sebuah skenario bisa saja menampilkan intelijen “tidak buta,” tetapi jembatan ke kebijakan dan operasi lapangan yang rapuh.
Di tingkat kepresidenan, tanggung jawabnya bersifat komando dan politis. Presiden memegang kendali atas BIN dan menetapkan prioritas keamanan nasional, termasuk pilihan strategi: apakah menenangkan gejolak dengan kanal dialog, koreksi kebijakan, dan komunikasi publik agresif; atau memusat pada penegakan hukum untuk menekan efek domino kekerasan. Dalam kasus sekarang, negara mengirim sinyal “ketegasan” di satu sisi dan janji evaluasi di sisi lain. Namun, sinyal itu belum menjadi “narasi pemersatu” yang mampu menurunkan suhu. Bila presiden lambat mengartikulasikan problem-inti yang memicu protes dalam hal ini isu tunjangan DPR dan rasa ketidakadilan maka kerja intelijen, secermerlang apa pun, akan sulit mencegah perluasan protes. Di masyarakat yang tersambung 24/7 oleh algoritma, kekosongan narasi resmi segera diisi oleh tafsir, sindiran, dan ajakan sebagian berniat baik, sebagian oportunistik.
Pertanyaannya kemudian, bukankah tugas BIN mengantisipasi semua ini? Ya, sejauh menyangkut deteksi, pemetaan aktor, dan rekomendasi opsi. Tetapi pencegahan kerusuhan bukanlah monopoli operasi tertutup. Ia bergantung pada desain pengamanan terbuka, kesiapan negosiator, kesiapan jalur evakuasi, tata kelola penggunaan kekuatan yang berjenjang, dan ini yang sering diabaikan arsitektur komunikasi publik yang proaktif. Aturan internal Polri tersedia: Perkap No. 1/2009 tentang penggunaan kekuatan, Perkap No. 16/2006 tentang pengendalian massa, Perkap No. 9/2008 tentang penyampaian pendapat di muka umum, Perkap No. 8/2010 tentang lintas ganti penanggulangan huru-hara. Kerangka ini, jika diikuti secara taat, memberi pagar agar gas air mata, peluru karet, water cannon, atau manuver kendaraan tak berubah menjadi pemantik krisis baru. Ketika pagar ini dilompati karena tekanan taktis atau salah kalkulasi yang runtuh bukan hanya barikade, tetapi juga legitimasi.
Fenomena “ada yang menunggangi” hampir selalu hadir dalam protes besar. Secara analitik, kita perlu membedakan tiga hal: provokasi spontan di lapangan, infiltrasi aktor yang memang berniat memantik kekerasan, dan generalisasi tanpa bukti yang hanya berfungsi sebagai tameng politik. Tanpa transparansi temuan intelijen (sepanjang tidak melanggar kerahasiaan yang dilindungi UU) dan tanpa rilis bukti forensik yang bisa diuji publik, narasi “penunggang” lebih banyak menambah noise ketimbang meredakan. Di titik ini, keterlibatan Komnas HAM, LBH, dan pemantau independen seharusnya dibaca pemerintah sebagai peluang untuk membangun kredibilitas, bukan ancaman. Ketika mereka mencatat penangkapan ratusan orang dan menyinggung dugaan ekses penggunaan kekuatan, jalur respons terbaik pemerintah adalah menjamin due process, membuka akses bantuan hukum, dan menyampaikan perkembangan investigasi dengan tenggat yang jelas.
Apakah Prabowo “kecolongan” dibanding dua presiden sebelumnya? Perbandingan lintas era sering menyesatkan karena variabelnya jauh berubah. Infrastruktur digital mempercepat mobilisasi, ekosistem media terfragmentasi, dan tingkat kepercayaan publik pada institusi formal pasang-surut mengikuti siklus politik. Ada juga dinamika orang-aktor: kepala BIN baru, komposisi kabinet, kepemimpinan Polri, dan hubungan pusat-daerah. Indikator yang lebih adil untuk menilai presiden mana pun adalah tiga hal: kecepatan pengakuan masalah (problem acknowledgment), kualitas desain respon (response design), dan ketekunan implementasi (execution stamina). Pada tiga indikator itu, pemerintahan hari ini belum optimal. Pengakuan masalah masih lebih banyak dalam bentuk penegasan menjaga ketertiban, padahal “akar” protes isu tunjangan, ketimpangan, dan keadilan prosedural perlu ditangani di ruang kebijakan dan komunikasi. Desain respon pun belum menunjukkan keseimbangan yang meyakinkan antara perlindungan hak berkumpul secara damai dengan pencegahan kekerasan. Sementara pada eksekusi, koordinasi intelijen-keamanan-komunikasi terlihat tersendat: di satu sisi ada penindakan cepat, di sisi lain informasi resmi yang lambat dan parsial memaksa publik mengandalkan serpihan kabar.
Di kubu intelijen, apa yang paling mungkin “gagal”? Kemungkinan pertama adalah bias normalitas membaca gejolak awal sebagai siklus rutin yang akan surut sendiri. Kemungkinan kedua adalah bottleneck koordinasi produk intelijen tidak menyatu dalam satu gambaran operasional yang komprehensif sehingga rekomendasi aksi dini (misalnya rekayasa lalu lintas, pembatasan waktu aksi, rute alternatif, staging area, penempatan negosiator senior, dan kesiapan trauma care) tidak dieksekusi menyeluruh. Kemungkinan ketiga adalah kurangnya “intelijen kelembagaan” di parlemen dan partai yakni jauhnya elite pembuat kebijakan dari radar sentimen publik sebelum kebijakan bergulir. Pada banyak negara demokrasi, fungsi intelijen kebijakan publik di sekitar parlemen dijalankan oleh unit riset dan lobi yang sensitif terhadap persepsi; ketika fungsi ini tumpul, keputusan yang secara formal sah bisa meledak secara sosial.
Lantas, bagaimana keluar dari spiral saling-menuding? Pertama, Presiden perlu mengambil alih narasi dengan mengakui akar masalah, menunda atau meninjau ulang kebijakan yang menjadi pemantik, dan ini krusial menetapkan standar keterbukaan data. Misalnya, jika isu tunjangan DPR yang memicu gejolak, tampilkan struktur anggaran rinci, proses pengambilan keputusan, dan skenario koreksi. Setelah itu, umumkan batas waktu audit peristiwa tewasnya Affan Kurniawan, dengan investigasi yang melibatkan pengawas eksternal dan rilis temuan berjenjang. Bukti yang transparan menurunkan suhu lebih cepat ketimbang seruan moral yang umum.
Kedua, perkuat “jembatan” intelijen aksi. Bentuk pusat fusi intelijen taktis untuk unjuk rasa yang menyatukan BIN, Intelkam Polri, BAIS TNI, dan pemda, dengan mandat tunggal: early warning to early action dalam horizon harian. Produk harian pusat ini harus memetakan titik rawan, kanal negosiasi, dan rencana kontingensi yang diikat SOP kepolisian tentang tahapan penggunaan kekuatan. Untuk mencegah bias eskalasi, masukkan “penjaga norma” dari Divisi Propam dan Itwasum serta penasihat HAM independen sebagai pengamat. Peta risiko dan keputusan harus terdokumentasi bukan untuk birokrasi melainkan untuk akuntabilitas post factum jika terjadi insiden.
Ketiga, optimalkan “penggalangan” dalam arti yang benar sebagaimana diamanatkan UU intelijen membangun jejaring kepercayaan dengan koordinator lapangan, serikat, komunitas, kampus, dan ormas. Penggalangan yang hanya dipahami sebagai kontra-narasi akan kalah cepat dari arus media sosial. Penggalangan yang efektif justru mengenali figur-figur yang dipercaya akar rumput untuk menurunkan tensi ketika garis massa mulai retak antara damai dan anarkis. UU 17/2011 menyediakan legitimasi untuk pendekatan ini selama dijalankan dengan penghormatan pada hukum dan tidak melanggar privasi atau menyusupkan provokasi.
Keempat, lakukan moratorium praktik-praktik berisiko tinggi sampai evaluasi tuntas: manuver kendaraan di kerumunan padat, tembakan gas air mata ke ruang tertutup atau ke arah massa tanpa koridor evakuasi, dan penggunaan peluru karet di jarak dekat. Perkap 1/2009 sudah memberi pagar tahapan penggunaan kekuatan; problem kita bukan kekurangan aturan, melainkan konsistensi mematuhinya. Laporan-laporan organisasi masyarakat sipil tentang ekses penggunaan senjata pengendali massa harus dijawab dengan tindakan korektif yang bisa diukur: modul pelatihan ulang, komando tunggal di lapangan, body-worn camera untuk satuan Dalmas, dan publikasi after action review untuk setiap insiden besar.
Kelima, jaga ruang informasi. Ketika media menayangkan gambar dramatis, itu bukan alasan untuk membungkam; justru menjadi panggilan bagi negara untuk hadir dengan data, kronologi, dan keputusan. Langkah Komnas HAM membuka posko pengaduan dan mempublikasikan temuan awal adalah praktik baik yang perlu diimbangi negara dengan rilis data resmi yang mudah diverifikasi. Upaya menekan media atau melarang liputan hanya akan memindahkan pertempuran ke kanal yang lebih liar dan tak terverifikasi.
Terakhir, kita harus jujur mengakui bahwa mencegah kerusuhan tidak identik dengan mencekik kebebasan. Negara yang kuat bukan negara yang tak pernah ada protes, melainkan negara yang protes besarnya tidak perlu dibayar dengan nyawa dan kebencian jangka panjang. Pada ukuran itu, kegagalan adalah kegagalan bersama: negara yang lambat mengakui dan memperbaiki, aparat yang tergelincir dari SOP, intelijen yang tidak cukup tajam mengubah peringatan menjadi aksi dini, elite yang menyepelekan getar bawah tanah, dan sebagian peserta aksi yang melanggar batas hukum. Peran Presiden di sini bukan sekadar “memerintahkan,” melainkan memimpin koreksi menata ulang koordinasi, mengoreksi kebijakan pemantik, mengembalikan kepercayaan pada aturan main, dan memastikan kepala-kepala lembaga kunci memikul tanggung jawabnya.
Apakah ini berarti BIN “gagal”? Jika ukuran tunggalnya adalah “tidak ada kerusuhan sama sekali,” maka hampir setiap lembaga intelijen di dunia akan dinyatakan gagal dalam berbagai episode sejarah. Ukuran yang lebih bernas adalah seberapa cepat sistem belajar dari kesalahan hari ini untuk mencegah eskalasi besok. Di sinilah Presiden dan Kepala BIN harus berdiri di depan: mengumumkan audit mandiri atas rantai intelijen kebijakan operasi terkait gelombang protes ini, merilis temuan yang tidak sensitif terhadap kerahasiaan operasi, dan menyampaikan timeline implementasi perbaikan. Transparansi parsial yang terukur jauh lebih kuat membangun ketertiban daripada komando yang seolah mahakuasa namun hampa bukti.
Menutup opini ini, biarkan publik menuntut dua hal sekaligus tanpa merasa bersalah: negara yang sigap melindungi hak berkumpul damai dan menindak pelaku kekerasan, serta lembaga intelijen yang tajam membaca tanda-tanda zaman namun rendah hati pada kontrol demokratis. Jika keduanya berjalan, kita tidak perlu lagi mendebat “kegagalan siapa,” karena keberhasilan mencegah korban dan memulihkan ketertiban akan menjadi jawabannya sendiri. (Hengki/DP)
Apa Reaksi Anda?