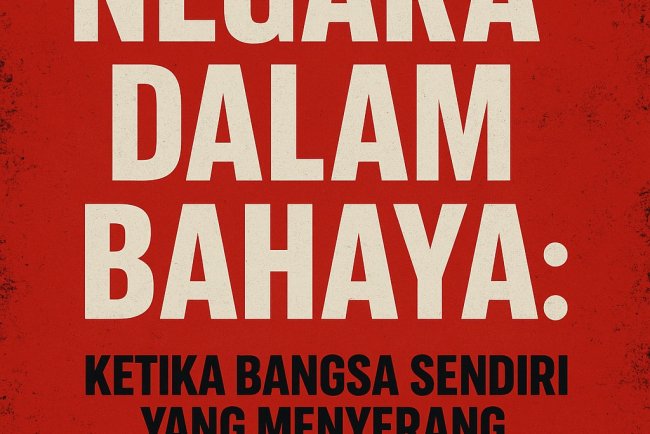Janji yang Terkubur di Istana: Prabowo, Korupsi, dan Kehormatan yang Memudar
Janji yang Terkubur di Istana: Prabowo, Korupsi, dan Kehormatan yang Memudar

detakpolitik.com, Jakarta - Di tengah gegap gempita kemenangan politiknya, Prabowo Subianto pernah berdiri di panggung kampanye dengan suara lantang, penuh keyakinan, dan sorot mata yang memancarkan janji besar: koruptor akan dibasmi tanpa kompromi, bahkan bila perlu diasingkan ke pulau terpencil seperti Nusa Kambangan. Janji itu diucapkan tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali, sebagai simbol komitmen moral dan politik yang menjadi magnet dukungan dari rakyat yang lelah melihat wajah-wajah pelaku korupsi mondar-mandir di layar televisi tanpa pernah benar-benar merasakan jeruji besi sebagai hukuman setimpal. Namun, seperti banyak janji politik yang lahir dari bibir para penguasa, ia kini terlihat tergeletak tak bernyawa di sudut ruang kekuasaan yang dingin.
Prabowo memasuki kursi kepresidenan dengan aura "pembawa perubahan", setidaknya itulah narasi yang dikemas oleh para pendukungnya. Narasi yang dibangun sedemikian rupa hingga publik mau percaya bahwa di tangannya, negeri ini akan melihat era baru dalam pemberantasan korupsi. Tapi, realitas politik adalah medan yang penuh dengan jebakan, dan janji itu, satu per satu, mulai dililit oleh kompromi dan kalkulasi kekuasaan. Bukannya memimpin perang melawan korupsi, Prabowo kini justru dihadapkan pada tuduhan mengibarkan bendera putih di hadapan para koruptor.
Kabar mengenai “amnesti jilid II” yang mencuat belakangan ini menjadi simbol telak dari pembalikan arah komitmen itu. Publik terperanjat mendengar bahwa ratusan tokoh, yang sebagian di antaranya punya jejak rekam kelam terkait penyalahgunaan kekuasaan dan dugaan korupsi, akan dibebaskan. Dalih rekonsiliasi, persatuan bangsa, dan kepentingan stabilitas politik disodorkan sebagai pembenaran. Namun, di balik retorika manis itu, aroma busuk transaksi politik tak dapat ditutupi. Rakyat yang dulu memandang Prabowo sebagai sosok tegas kini melihat bayangan seorang presiden yang melunak di hadapan elite, bahkan tunduk pada tekanan lingkaran kekuasaan yang selama ini menjadi lahan subur praktik korupsi.
Pertanyaannya, bagaimana seorang presiden yang dulu menuding para koruptor sebagai musuh bangsa, kini justru memberi karpet merah kepada mereka untuk kembali menghirup udara bebas? Apakah janji itu sejak awal hanyalah alat kampanye untuk meraih simpati rakyat? Atau kekuasaan memang sedemikian kuat memutarbalikkan niat baik, hingga seorang pemimpin yang digadang-gadang tegas pun berakhir sebagai penjaga status quo?
Sejarah politik Indonesia tak kekurangan contoh pemimpin yang gagal menepati janji. Namun, kekecewaan kali ini terasa lebih menusuk karena harapan yang ditanam begitu tinggi. Prabowo tampil di masa di mana rakyat muak melihat korupsi merajalela, di mana indeks persepsi korupsi Indonesia stagnan, dan lembaga penegak hukum kerap kehilangan taringnya. Harapan itu kini terkikis, digantikan rasa getir melihat seorang pemimpin justru memilih jalan kompromi. Bukannya membersihkan meja makan kekuasaan dari tikus-tikus yang rakus, ia justru memberi kursi baru bagi mereka di pesta politik.
Ada yang mencoba membela, mengatakan bahwa langkah ini adalah bentuk rekonsiliasi nasional, bahwa mengampuni para tokoh yang bermasalah adalah cara untuk meredam gejolak politik. Tapi bukankah rekonsiliasi sejati lahir dari keadilan, bukan dari penghapusan dosa tanpa konsekuensi? Apa artinya hukum bila ia hanya berlaku keras bagi rakyat kecil yang mencuri demi makan, tetapi berubah lentur bagi para elite yang merampas miliaran uang negara? Di sini, bukan hanya persoalan moral pribadi presiden yang dipertaruhkan, melainkan juga kredibilitas negara di mata rakyatnya.
Tak dapat dipungkiri, politik memang kerap memaksa kompromi. Tetapi ada garis merah yang bila dilangkahi akan menghapus kepercayaan publik. Pemberian amnesti massal kepada mereka yang pernah menjadi bagian dari masalah korupsi adalah garis merah itu. Saat presiden melangkahinya, pesan yang diterima rakyat adalah: korupsi bisa dimaafkan asal Anda punya posisi, koneksi, atau nilai tukar politik yang cukup. Pesan ini berbahaya, bukan hanya untuk masa kini, tapi juga untuk generasi mendatang yang akan tumbuh dengan keyakinan bahwa integritas dapat diperjualbelikan.
Kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa sebagian besar rakyat tidak pernah meminta rekonsiliasi model ini. Mereka meminta keadilan. Mereka ingin melihat bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, bahwa janji kampanye bukan sekadar retorika. Mereka ingin seorang presiden yang berdiri di atas prinsip, bukan di atas perhitungan politik sempit. Sayangnya, langkah Prabowo justru menunjukkan bahwa di republik ini, janji hanyalah komoditas musiman, dan koruptor tetap menjadi tamu terhormat selama mereka punya nilai strategis di meja kekuasaan.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan yang lebih dalam tentang arah bangsa ini. Bila presiden yang seharusnya menjadi panglima perang melawan korupsi justru menurunkan senjata, siapa yang akan melanjutkan pertempuran ini? Apakah kita harus pasrah melihat hukum menjadi alat negosiasi politik? Apakah keadilan akan terus menjadi kata yang indah di pidato, tetapi kosong dalam praktik? Dan lebih jauh lagi, apakah rakyat akan terus membiarkan dirinya diperdaya oleh janji-janji manis yang berakhir pahit?
Opini publik yang berkembang saat ini tidak lagi sekadar kekecewaan, melainkan kemarahan yang perlahan memupuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Prabowo, dalam posisinya sekarang, memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa tuduhan tunduk kepada para koruptor adalah keliru. Namun, setiap langkah yang diambilnya akan menjadi catatan sejarah. Dan jika ia memilih untuk terus melangkah di jalur kompromi ini, sejarah akan menulisnya bukan sebagai presiden yang menuntaskan janji perang melawan korupsi, melainkan sebagai pemimpin yang menguburnya di bawah meja perundingan dengan para pelaku yang seharusnya ia lawan.
Kini, bola ada di tangannya. Ia bisa memutar arah, menegaskan kembali bahwa hukum berdiri di atas kepentingan politik, atau membiarkan dirinya diingat sebagai presiden yang menukar integritas dengan stabilitas semu. Namun satu hal yang pasti, rakyat tidak akan mudah melupakan saat seorang pemimpin, yang dulu dielu-elukan sebagai sosok tegas dan berani, memilih berlutut di hadapan mereka yang pernah merampas masa depan bangsa. Janji itu pernah membakar semangat jutaan orang. Dan kini, abu dari janji itu bertebaran, menjadi saksi bahwa di negeri ini, bahkan kata-kata yang terucap dengan lantang pun bisa sirna di telan bisu kekuasaan. (dodo/dp)
Apa Reaksi Anda?