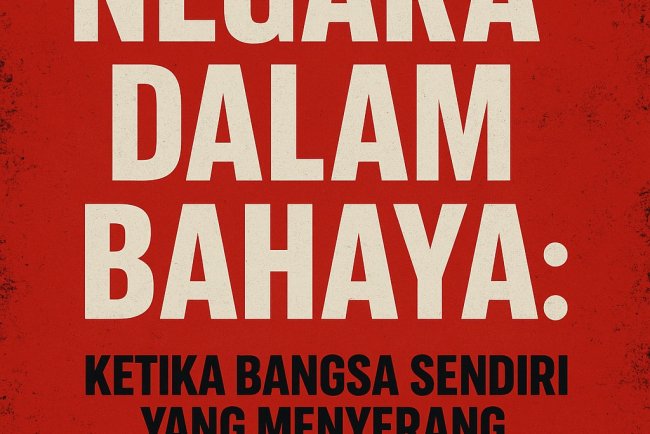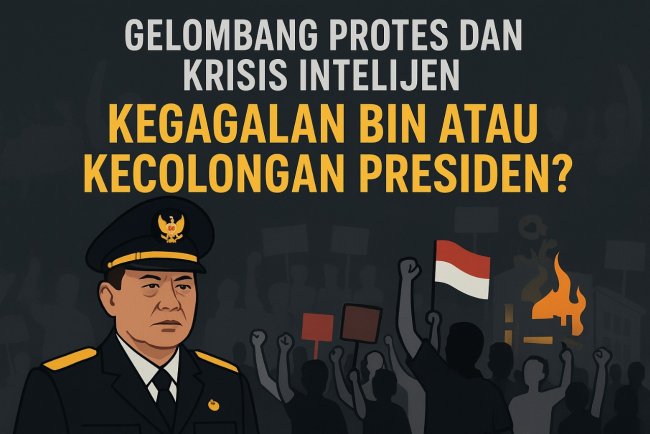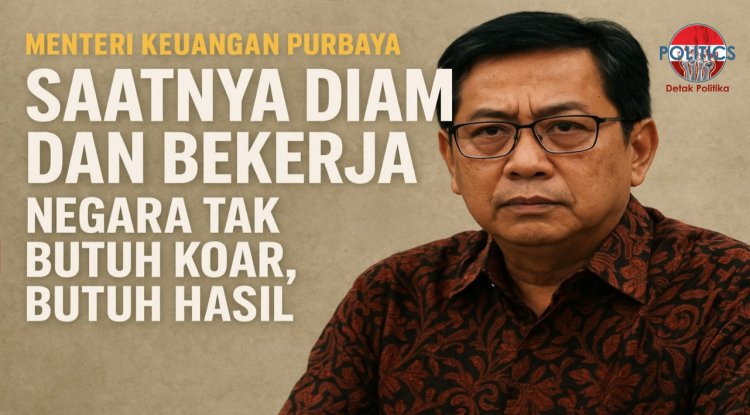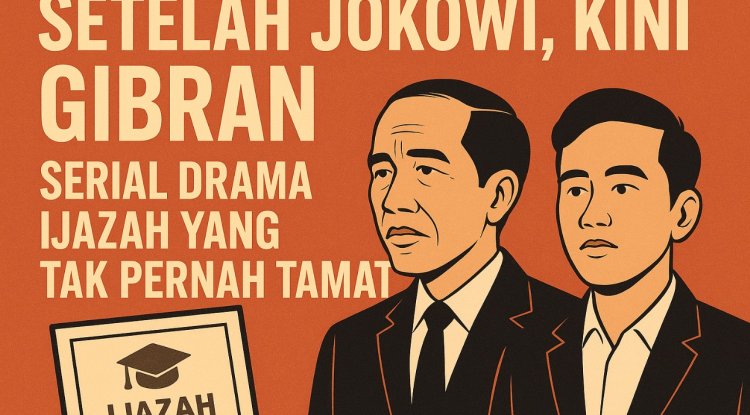Reshuffle Prabowo 2025: Antara Keberanian Politik dan Bahaya Krisis Fiskal
Reshuffle Kabinet Prabowo Subianto dan Bayangan Sejarah Indonesia

detakpolitik.com, Jakarta - Reshuffle kabinet selalu menjadi momen yang ditunggu, ditafsirkan, bahkan ditakuti dalam politik Indonesia. Ia bukan sekadar pergantian pejabat negara, melainkan cermin dari pergeseran kekuasaan, arah kebijakan, hingga tarikan kepentingan di belakang layar. Pada 8 September 2025, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle besar yang segera mengguncang arena politik nasional, memicu reaksi pasar internasional, dan menyalakan perdebatan publik. Keputusan mencopot Sri Mulyani Indrawati dari kursi Menteri Keuangan, membentuk Kementerian Haji dan Umrah, hingga mengosongkan sementara jabatan Menko Polhukam, semuanya menandakan bahwa reshuffle kali ini bukan sekadar kosmetik. Ia adalah langkah politik yang sarat risiko, penuh kalkulasi, dan tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah panjang praktik reshuffle di Indonesia sejak masa Orde Baru.
Untuk memahami dampak reshuffle Prabowo, penting melihat ke belakang, bagaimana presiden-presiden sebelumnya menggunakan instrumen reshuffle untuk mengelola kekuasaan. Soeharto, misalnya, memanfaatkan reshuffle sebagai mekanisme kontrol dan konsolidasi. Pada era Orde Baru, reshuffle jarang dihubungkan dengan evaluasi kinerja, melainkan lebih sebagai sarana untuk menjaga loyalitas dan menyeimbangkan kekuatan di antara militer, teknokrat, dan Golkar. Soeharto piawai memainkan peran: para teknokrat seperti Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, dan Emil Salim dipertahankan selama puluhan tahun untuk menjaga stabilitas ekonomi, sementara jenderal-jenderal militer digeser dari satu jabatan ke jabatan lain untuk mencegah munculnya kekuatan tandingan. Bagi Soeharto, reshuffle adalah ritual kekuasaan yang penuh simbol sekaligus sarana untuk menunjukkan siapa yang masih dipercayai, siapa yang sedang diuji, dan siapa yang sudah habis masa pakainya. Reshuffle pada masa itu jarang menimbulkan kejutan di pasar internasional karena struktur politik sangat terkendali dan stabilitas dianggap terjamin.
Memasuki era Reformasi, praktik reshuffle mengambil makna baru. Susilo Bambang Yudhoyono, presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat, menggunakan reshuffle sebagai instrumen manajemen politik sekaligus alat komunikasi dengan pasar. SBY dikenal sering menggunakan reshuffle untuk merespons isu-isu tertentu, meski gaya kepemimpinannya cenderung hati-hati dan penuh kalkulasi. Dalam dua periode pemerintahannya, ia beberapa kali mengganti menteri ekonomi untuk menjaga keseimbangan antara partai politik koalisi dan kepentingan teknokratis. Publik kadang menilai reshuffle era SBY kurang berdampak signifikan karena terlalu kompromistis, tetapi investor melihatnya sebagai tanda bahwa pemerintah berusaha menjaga kredibilitas. Di bawah SBY, Indonesia relatif stabil secara ekonomi, meski tak jarang reshuffle hanya memindahkan loyalis politik tanpa membawa perubahan substantif.
Joko Widodo menghadirkan dinamika berbeda. Sebagai presiden yang lahir dari kultur politik lokal dan bukan elit tradisional, Jokowi menggunakan reshuffle sebagai panggung untuk menunjukkan kedaulatannya terhadap partai pendukung. Pada periode pertamanya, ia kerap mengganti menteri yang dianggap menghambat visinya dalam pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi. Jokowi tidak segan mencopot tokoh partai, bahkan dari PDIP yang menjadi basis utamanya, jika dianggap tidak sejalan. Salah satu reshuffle paling bersejarah adalah masuknya Sri Mulyani kembali ke kabinet pada 2016 setelah lama berkiprah di Bank Dunia. Kehadirannya langsung dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat kredibilitas ekonomi Indonesia di mata internasional. Jokowi juga memanfaatkan reshuffle untuk mengakomodasi partai-partai baru dalam koalisi, seperti Golkar dan PAN, menunjukkan bahwa reshuffle baginya adalah instrumen negosiasi politik yang fleksibel sekaligus alat mengelola stabilitas. Dalam dua periode Jokowi, reshuffle tidak hanya dipicu oleh masalah kinerja, tetapi juga menjadi cermin dari “politik dagang sapi” dalam sistem multipartai Indonesia.
Kini, di era Prabowo Subianto, reshuffle kembali dimaknai secara berbeda. Prabowo datang ke kursi presiden dengan latar belakang panjang sebagai militer sekaligus politisi yang terbiasa berjuang dari luar lingkaran kekuasaan. Sejak awal pemerintahannya, ia menekankan visi besar tentang ketahanan nasional, kedaulatan pangan, dan program sosial berskala luas. Namun, realitas ekonomi dan politik yang dihadapinya tidak sederhana. Program makan siang gratis, misalnya, membutuhkan pembiayaan triliunan rupiah yang tidak mungkin ditopang hanya dengan disiplin fiskal ketat ala Sri Mulyani. Maka, pencopotan Sri Mulyani dan pengangkatan Purbaya Yudhi Sadewa mencerminkan pergeseran filosofi: dari menjaga kredibilitas jangka panjang menuju keberanian menempuh ekspansi fiskal demi pertumbuhan jangka pendek dan kepentingan politik. Bagi Prabowo, rakyat membutuhkan hasil yang cepat, dan kabinet harus diisi oleh orang-orang yang bersedia mengeksekusi visi tersebut tanpa terlalu banyak keberatan teknokratis.
Namun risiko dari langkah ini besar. Sri Mulyani adalah figur yang dihormati dunia internasional. Selama bertahun-tahun ia menjadi jembatan antara pemerintah Indonesia dan lembaga keuangan global. Kehilangannya membuat pasar meragukan komitmen Indonesia terhadap disiplin fiskal. Reaksi langsung terlihat pada penurunan indeks saham dan gejolak rupiah. Investor asing, yang sebelumnya melihat Indonesia sebagai tempat aman untuk menanam modal, kini mulai berhitung ulang. Pertanyaan muncul: apakah Indonesia akan tetap menjaga defisit di bawah tiga persen PDB, ataukah aturan itu akan dilonggarkan demi membiayai ambisi-ambisi populis? Apakah utang akan meningkat pesat hingga membebani generasi mendatang? Atau justru ekspansi fiskal bisa membawa lonjakan pertumbuhan yang memberi manfaat lebih besar?
Konteks sosial tidak kalah penting. Reshuffle ini dilakukan setelah gelombang protes rakyat yang menentang tunjangan besar anggota DPR. Demonstrasi berdarah di Jakarta dan beberapa kota lain menjadi latar belakang yang tidak bisa diabaikan. Publik menilai elit politik terlampau jauh dari penderitaan rakyat kecil. Dalam situasi itu, reshuffle menjadi pesan simbolis bahwa Prabowo mendengar suara rakyat. Dengan mencopot figur-figur yang dianggap mewakili elit lama, presiden berusaha menunjukkan keberpihakan. Namun sejarah mengajarkan bahwa reshuffle tidak otomatis memulihkan kepercayaan rakyat jika kebijakan nyata di lapangan tidak berubah. Pada era Jokowi, misalnya, reshuffle yang membawa tokoh populer ke kabinet tidak selalu meningkatkan kepuasan publik, karena rakyat lebih peduli pada harga kebutuhan pokok daripada wajah baru menteri. Di era SBY, reshuffle bahkan sering dianggap basa-basi karena tidak berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Jika pola itu terulang, reshuffle Prabowo pun berpotensi hanya menjadi hiburan politik tanpa makna substantif.
Di bidang politik praktis, reshuffle ini juga memperlihatkan pola konsolidasi kekuasaan. Penunjukan Ferry Juliantono dan Dahnil Anzar Simanjuntak, dua figur yang jelas berada dalam lingkaran Prabowo, memperkuat kesan bahwa kabinet kini lebih loyal kepada presiden daripada kepada partai koalisi. Ini bisa memperkuat stabilitas internal, tetapi juga menimbulkan ketegangan dengan partai politik yang merasa dikurangi pengaruhnya. Sejarah menunjukkan bahwa dalam sistem multipartai Indonesia, presiden harus lihai menjaga keseimbangan. SBY berhasil mempertahankan koalisi besar selama dua periode dengan memberi ruang kepada partai. Jokowi, meski lebih dominan, tetap memberi kompensasi kepada mitra koalisi melalui reshuffle. Jika Prabowo terlalu menutup ruang dan hanya mengisi kabinet dengan loyalis, ia berisiko memicu gesekan politik yang bisa melemahkan dukungan di parlemen.
Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah adalah dimensi lain yang menarik. Secara simbolis, langkah ini memperlihatkan perhatian besar pemerintah terhadap aspirasi umat Islam. Ia bisa memperkuat legitimasi politik Prabowo di mata kelompok religius. Namun pembentukan kementerian baru juga menimbulkan kritik tentang pembengkakan birokrasi. Di tengah kebutuhan untuk efisiensi anggaran, apakah bijak menambah struktur baru? Apakah pelayanan haji benar-benar membaik atau justru semakin rumit dengan birokrasi tambahan? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi ujian bagi kementerian baru tersebut, dan kegagalannya bisa mencoreng kredibilitas pemerintah.
Dalam perspektif masa depan, reshuffle 2025 ini bisa dibaca sebagai pertarungan arah bangsa. Jika berhasil, ia bisa menjadi titik balik menuju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, pelayanan publik yang lebih responsif, dan stabilitas politik yang kuat. Namun jika gagal, ia bisa menjadi awal dari krisis fiskal, ketidakstabilan sosial, dan melemahnya legitimasi pemerintah. Skenarionya bisa beragam. Dalam skenario optimistis, Purbaya mampu menjaga keseimbangan antara ekspansi fiskal dan disiplin anggaran, investor kembali percaya, rakyat merasakan manfaat program populis, dan kabinet yang loyal berhasil mengeksekusi program dengan cepat. Dalam skenario pesimistis, belanja negara membengkak, inflasi naik, rupiah tertekan, rakyat tetap menderita, sementara program populis hanya menjadi proyek pencitraan yang gagal. Dalam skenario moderat, pemerintah berhasil menjaga stabilitas jangka pendek, tetapi gagal melakukan reformasi struktural, sehingga Indonesia kembali pada jebakan pertumbuhan lima persen tanpa perubahan mendasar.
Dalam sejarah Indonesia, reshuffle selalu membawa harapan dan kecemasan sekaligus. Dari Soeharto yang menggunakannya sebagai alat kontrol, SBY yang menjadikannya instrumen kompromi, Jokowi yang memanfaatkannya sebagai panggung kedaulatan politik, hingga Prabowo yang kini menggunakannya sebagai simbol keberanian mengambil risiko. Setiap era menghadapi tantangan berbeda, tetapi benang merahnya sama: reshuffle adalah cermin dari tarik-menarik antara politik, ekonomi, dan sosial. Pertanyaannya sekarang, apakah reshuffle Prabowo 2025 akan tercatat dalam sejarah sebagai langkah berani yang membuka jalan menuju kemajuan, ataukah sebagai awal dari serangkaian krisis baru yang membawa Indonesia ke dalam turbulensi? Jawabannya akan bergantung pada bagaimana para menteri baru bekerja, bagaimana presiden mengelola koalisi, dan bagaimana rakyat merespons kebijakan nyata yang menyentuh kehidupan mereka sehari-hari. (hengki/DP)
Apa Reaksi Anda?